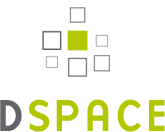Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/103342| Title: | Pemanfaatan Cendana (Santalum album Linn.) Oleh Masyarakat Mukim di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie |
| Authors: | Matangaran, Juang Rata Santosa, Gunawan Suharjito, Didik Sari, Rita Kartika Nurochman, Deden |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pemanfaatan cendana asal Provinsi Aceh yang dilakukan secara intensif setelah tahun 2000-an dan diperdagangkan ke industri pengolahan cendana dengan mengatasnamakan cendana asal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pemanfaatan cendana oleh masyarakat dilakukan dengan memasarkan cendana dalam bentuk gubal cendana (kayu bulat kecil) tanpa adanya strategi kebijakan untuk memanfaatkan cendana secara berkelanjutan. Cendana merupakan hasil hutan dengan nilai ekonomi tinggi yang memiliki penyebaran spesifik di wilayah timur Indonesia, antara lain: Provinsi NTT, Bali, Jawa Timur, Yogyakarta, Sulawesi Tengah dan Maluku. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk merumuskan konsep pemanfaatan cendana secara berkelanjutan. Tujuan utama tersebut dapat dipenuhi melalui pencapaian tujuan antara, yaitu: (1) Menganalisis asal-usul keberadaan dan keragaman genetik cendana asal Provinsi Aceh serta hubungan kekerabatannya dengan cendana Provinsi NTT; (2) Menjelaskan potensi dan struktur tegakan, teknik pengelolaan serta efisiensi pemanenan cendana yang dilakukan Masyarakat Mukim; (3) Menganalisis hubungan kualitas cendana berdasarkan diameter pohon dan proporsi kayu terasnya; (4) Menganalisis pola dan kinerja saluran pemasaran cendana; dan (5) Menjelaskan peran dan efektivitas kelembagaan KPH dan Mukim dalam pengelolaan sumberdaya cendana. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kuta Malaka dan Sungai Makmur di Kabupaten Aceh Besar serta di Kecamatan Muara Tiga dan Padang Tiji di Kabupaten Pidie dari bulan April 2017 sampai bulan Januari 2018. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, wawancara semi terstruktur, wawancara terstruktur, wawancara mendalam, studi dokumentasi, pengukuran, pengambilan sampel uji dan analisis laboratorium. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel secara sengaja (purposive sampling) yang terkait dengan atribut cendana. Penelitian ini mengkombinasikan dua pendekatan, yaitu: pendekatan pengelolaan hutan (timber management) dan pendekatan kelembagaan. Berdasarkan kedua pendekatan tersebut maka penelitian ini mengkaji pemanfaatan cendana kedalam empat sub-sistem, meliputi: pengelolaan, pengolahan, pemasaran dan kelembagaan (struktur dan norma). Analisis data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Populasi cendana yang ada di Kabupaten Aceh Besar dan Pidie berasal dari Provinsi NTT, dengan pusat keragaman genetik cendana berada di populasi Suka Makmur dan Padang Tiji. (2) Teknik pengelolaan cendana yang dilakukan belum menjamin keberlanjutan cendana dengan struktur tegakan cendana didominasi tegakan muda, proporsi tingkat induk terhadap anakan rendah serta tidak adanya kegiatan persemaian dan penanaman, melainkan hanya pemeliharaan, perlindungan dan pemanenan pohon cendana. Teknik pemanenan pohon cendana menggunakan metode tree lenght logging plus akar dengan tingkat efisiensi pemanenan cendana yang rendah. (3) Cendana asal Aceh yang memenuhi standar mutu untuk tujuan penggunaan kerajinan kayu dan minyak atsiri cendana berasal dari pohon cendana dengan diameter pohon (dbh) minimal 15 cm dengan proporsi kayu teras minimal 48.53% Cendana untuk penggunaan dupa wangi diutamakan dari limbah (sisa) pemanenan pohon (batang, cabang dan ranting) dan ampas serbuk cendana hasil penyulingan. (4) Lembaga-lembaga pemasaran cendana, terdiri atas: petani, pedagang pengumpul lokal, pedagang pengumpul provinsi, pembeli lain dan industri yang membentuk tiga pola saluran pemasaran. Secara umum kinerja saluran pemasaran produk cendana belum mengarah kepada bentuk pasar yang efisien. Saluran pemasaran cendana dengan rantai pemasaran yang pendek menghasilkan kinerja pemasaran yang lebih baik. (5) Sumberdaya cendana yang dimanfaatkan Masyarakat Mukim memiliki karakteristik private property dan communal property. KPH dan Mukim belum mampu secara efektif mengatur pengelolaan sumberdaya cendana yang dilakukan oleh Masyarakat Mukim secara berkelanjutan. Cendana belum melembaga bagi KPH disebabkan tidak masuk dalam rencana pengelolaan hutan (RPHJP). Pengelolaan sumberdaya cendana sebagai bagian dari Adat uteun juga belum secara optimal dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat. Pengaruh pihak luar lembaga Mukim dalam pengelolaan cendana sangat dominan yang menyebabkan performansi (struktur dan proporsi) cendana yang rendah pada tingkat induk (tiang dan pohon). Nilai kebaruan yang diperoleh dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) asal-usul keberadaan, keragaman genetik dan hubungan kekerabatan cendana asal Provinsi Aceh dengan cendana asal Provinsi NTT; 2) teknik pengelolaan cendana yang dilakukan oleh masyarakat lokal di luar wilayah Provinsi NTT, spesifik bagi Masyarakat Mukim di Provinsi Aceh; 3) penentuan pohon cendana layak tebang berdasarkan diameter pohon dan proporsi kayu terasnya; 4) pola dan kinerja pemasaran cendana yang ada di luar wilayah Provinsi NTT, spesifik di Provinsi Aceh; 5) rekomendasi kelembagaan pemanfaatan cendana secara berkelanjutan. Implikasi teoritik dalam pemanfaatan cendana berdasarkan pendekatan pengelolaan hutan (timber management) dan kelembagaan untuk mencapai pengelolaan cendana secara berkelanjutan yaitu diperlukan sinergitas konsep pengelolaan hutan dan konsep kelembagaan dalam setiap pemanfaatan sumberdaya hutan. Hal ini disebabkan pemanfaatan cendana oleh Masyarakat Mukim belum dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan konsep pengelolaan hutan dan kelembagaan. Konsep pengelolaan hutan menunjukkan bahwa pemanfaatan cendana (pengelolaan, pengolahan dan pemasaran) oleh masyarakat Mukim masih berada pada tingkat peralihan menuju konsep timber management. Konsep kelembagaan dalam pemanfaatan cendana oleh Masyarakat Mukim menunjukkan bahwa KPH dan Mukim belum efektif mengatur Masyarakat Mukim dalam mengelola sumberdaya cendana secara berkelanjutan. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/103342 |
| Appears in Collections: | DT - Forestry |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20019dnu.pdf Restricted Access | Fulltext | 48.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.