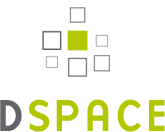Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/98580| Title: | Peran dan Relasi Aktor dalam Resiliensi Komunitas Menghadapi Bencana Kebakaran Hutan. |
| Authors: | Pandjaitan, Nurmala K Sumarti, Titik Tabenu, Oktovianus |
| Issue Date: | 2019 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Tujuan penelitian yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan sumber daya yang dimanfaatkan komunitas. (2) Menganalisis kapasitas adaptasi komunitas dalam menghadapi bencana kebakaran hutan. (3) Mengidentifikasi dan menganalisis nilai sosial ekonomi hutan bagi komunitas sekitar. (4) Mengidentifikasi dan menganalisis resiliensi komunitas dalam menghadapi bencana kebakaran hutan. (5) Mengidentifikasi dan menganalisis peran dan relasi aktor dalam resiliensi komunitas menghadapi bencana kebakaran hutan. Penelitian dilakukan di suatu komunitas pemanfaat sumberdaya hutan yang terkena bencana kebakaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, selama 2 bulan dari April 2018-Juni 2018. Sumber daya hutan memiliki potensi yang dimanfaatkan komunitas untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kebakaran hutan yang meluas di Sumatera Selatan merupakan bencana bagi masyarakat sekitar kawasan hutan namun, disisi lain kondisi ini memiliki manfaat positif untuk kegiatan bersawah sonor. Kebakaran hutan dan kebijakan pemerintah tentang pelarangan membakar hutan dan atau lahan memberikan dampak yang merugikan bagi komunitas karena, membatasi akses mereka untuk memanfaatkan potensi hutan sebagai sumber nafkah maupun sumber pangan. Komunitas harus berusaha menyesuaikan diri pada kondisi yang baru agar dapat tetap berfungsi. Proses adaptasi ini tentu tidak mudah karena, selama ini komunitas sangat bergantung pada hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat kekuatan sumber daya hutan dan kapasitas adaptasi komunitas untuk dapat resilien. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang didukung data kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa hutan adalah sumber mata pencaharian utama komunitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sudah mulai berkurang. Padi sonor tidak dapat lagi diproduksi karena adanya perda nomor 6 tahun 2016 yang melarang rakyat bercocok tanam dihutan, tanaman hutan lainnya sudah sangat berkurang karena hutan berubah fungsi menjadi perkebunan. Produksi karet berkurang akibat hawa panas dari kebakaran. Selanjutnya kapasitas adaptasi komunitas tergolong kurang karena meskipun sudah berulang kali mengalami kebakaran tidak ada suatu perubahan atau cara baru yang dilakukan komunitas untuk mengatasi minimnya sumber daya pangan. Keterkaitan dengan pihak luar tidak terlalu berdampak pada bertumbuhnya peluang-peluang ekonomi baru. Nilai sosial hutan memberikan makna persatuan kepada komunitas Perigi secara turun-temurun. Keberadaan hutan mengkonstruk komunitas untuk bertindak kreatif melalui pengetahuan lokal (local knowledge) dalam memanfaatkan potensi yang terkandung di dalamnya. Komunitas memiliki pengetahuan lokal yang dikenal dengan istilah huma sebagai suatu tradisi membuka lahan kering (talang) sedangkan sonor untuk membuka lahan rawa. Selain itu kepercayaan komunitas terhadap hutan melalui kebiasaan ritual masih tetap ada sampai saat ini. Fungsi dari tradisi-tradisi ini adalah untuk tetap menjaga keberlanjutan hutan melalui ungkapan dan aturan lisan untuk membatasi pengrusakan hutan secara liar. Pengetahuan lokal komunitas dalam memanfaatkan potensi hutan mengandung makna kekeluargaan dan kebersamaan. Sistem kekeluargaan yang terkandung dalam tradisi lokal mulai pudar akibat campur tangan pihak luar seperti penerapan peraturan pemerintah yang mengabaikan tatanan sosial komunitas disekitar hutan. Sementara itu potensi hutan yang beragam memiliki nilai ekonomi berupa hasil produksi kayu-kayuan berkualitas, hasil produksi lahan kering (talang) seperti tanaman pangan dan perkebunan karet dan hasil produksi lahan rawa seperti tanaman padi. Komunitas Perigi selama ini menggantungkan hidup pada potensi yang dimiliki tersebut. Namun, hasil produksi kayu sekarang semakin berkurang akibat terjadinya degradasi hutan karena kebakaran luas. Hasil padi rawa hanya untuk memenuhi ketersediaan beras dalam keluarga bukan untuk dikomersialisasikan. Komunitas Perigi lebih dominan mengharapkan hasil tanaman karet untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga baik kebutuhan sandang, pangan, dan papan maupun kebutuhan lainnya. Keragaman sumber daya alam yang ada bernilai ekonomis tinggi namun, tidak dimaksimalkan secara efisien oleh komunitas karena kualitas sumber daya manusia yang terbatas. Selain itu kepemilikan lahan yang sempit menyulitkan komunitas untuk mengakses potensi alam secara luas dalam meningkatkan kebutuhan ekonomi. Peran aktor sebagai penguat adaptasi komunitas Perigi dalam mengahadapi bencana kebakaran hutan. Pada komunitas Perigi terdapat tiga pemangku kepentingan yang berperan aktif menggerakan pembangunan desa yaitu Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan Tokoh masyarakat. Relasi aktor formal (Kepala Desa) memiliki relasi struktural dengan aparatur desa untuk kepentingan dukungan legalisasi kebijakan program-program pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya. Relasi Kepala Desa dengan aparatur desa yang dimaksud yakni Bendahara Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kaur Pembangunan. Sedangkan secara non struktural aktor formal (Kepala Desa) membangun relasi dengan kelompok preman (pencurian/begal), kelompok pemuda melalui hubungan pertemanan untuk kepentingan ketertiban dan keamanan desa. Hal ini mampu meredam kejadian ganguan kemalingan, penodongan, yang sering terjadi di wilayah sekitar Pangkalan Lampam. Selanjutnya aktor non formal (Tokoh Masyarakat) juga membangun relasi struktural dengan sebagian aparatur desa yakni, Sekertaris Desa, Kaur Pemerintahan, Kepala Dusun. Selain itu tokoh agama, dan sebagian besar kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok pengrajin, kelompok masyarakat gambut peduli kebakaran (KMGPK), kelompok peternak ikan. Relasi ini dibangun atas kepentingan untuk pembangunan desa melalui pemanfaatan program-program pemberdayaan di desa. Selain itu aktor non formal membangun relasi dengan aparatur pemerintahan untuk kepentingan pengurusan administrasi yang dibutuhkan dari LSM atau instansi pemerintahan terkait pemanfatan program di desa. Secara keseluruhan persaingan yang terjadi dalam komunitas perigi ini memiliki tujuan untuk memberfungsikan resiliensi komunitas Perigi dalam mengahadapi bencana kebakaran hutan. Aktor non formal (tokoh masyarakat) dan aktor formal (Kepala Desa dan aparatur desa) tersebut berperan diarenanya masing-masing. Kepala Desa lebih kepada pengelolaan kebijakan-kebijakan pembangunan, misalnya tentang pemanfaatkan dana desa dan pengelolaan aset-aset desa termasuk urusan-urusan politik di desa, sementara tokoh masyarakat lebih memfokuskan pada arena ekonomi yaitu menggerakan masyarakat melalui pemanfaatan program pemberdayaan. Kurang efektifnya peran aktor adalah salah satu penyebab utamanya. Resiliensi komunitas Perigi baru berada pada ranah stabilitas. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/98580 |
| Appears in Collections: | MT - Human Ecology |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2019ota.pdf Restricted Access | 36.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.