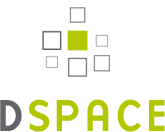Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/95968| Title: | Pengelolaan Kawasan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan Berdasarkan Keterpaduan Perikanan Tangkap dan Keramba Jaring Apung Ikan Kerapu. |
| Authors: | Yulianda, Fredinan Boer, Mennofatria Nurjaya, I Wayan Adibrata, Sudirman |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Pemanfaatan kawasan pulau-pulau kecil pada ekosistem terumbu karang dapat berupa ekstraksi jasa ekosistem seperti sumberdaya ikan karang, ikan kerapu sunu (Plectropomus maculatus Bloch 1790), yang berasosiasi dengan terumbu karang. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun strategi pengelolaan perikanan kerapu berkelanjutan secara spasial dan temporal melalui pengaturan zonasi untuk zona perlindungan, daerah penangkapan ikan (fishing ground), dan zona budidaya keramba jaring apung (KJA), pengaturan musim perlindungan dan penangkapan ikan kerapu sunu, serta pengaturan kelayakan usaha perikanan tangkap ikan kerapu. Batasan lokasi penelitian menjadi batasan spasial yaitu antara Pulau Lepar dan Pulau Pongok Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dasar pendekatan ekologi, sosial, dan ekonomi yaitu dengan mempertimbangkan aspek biofisik lingkungan perairan dan sumberdaya ikan kerapu sunu, serta perhitungan kelayakan usaha nelayan. Metode penelitian yaitu dengan mencari nilai tingkat eksploitasi (E). Selanjutnya, metode untuk mengetahui zona perlindungan berdasarkan kondisi ikan kerapu sunu saat memijah pada Musim barat dan Peralihan I (Desember - Mei) serta Musim timur dan Peralihan II (Juni - Nopember), masing-masing selama enam bulan. Analisis spasial dengan Marxan dimana ada tujuh parameter sebagai fitur konservasi dan empat parameter sebagai fitur biaya. Spasial untuk budidaya KJA dengan metode overlay parameter bioteknis lingkungan diperoleh dari penelitian sebelumnya. Analisis temporal menggunakan lima parameter untuk mengetahui puncak musim pemijahan ikan. Analisis kelayakan usaha perikanan tangkap dengan menghitung Revenue per Cost Ratio (R/C) dan Payback Period (PP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai mortalitas alami (M), mortalitas total (Z), mortalitas penangkapan (F), dan eksploitasi (E) diperoleh nilai masing-masing 0.50; 2.29; 1.80; 0.78 dengan R2 sebesar 0.98. Berdasarkan Gulland (1983), diketahui dari nilai di atas jika Foptimum sama dengan M maka tingkat eksploitasi akan optimum (Eoptimum) yaitu saat mencapai 0.50. Fakta di lapangan bahwa nilai tingkat eksploitasi (E) 0.78 lebih dari 0.50 maka dinyatakan sudah terjadi over-eksploitasi di lokasi penelitian. Kondisi ini menuntun pada perlunya pemanfaatan kawasan dengan pengaturan spasial dan temporal yang menguntungkan perikanan dan konservasinya. Pengaturan zonasi untuk zona perlindungan pada Musim barat dan Peralihan I diperoleh luas 24.39 km2, pada Musim timur dan Peralihan II diperoleh luas total 16.75 km2 pada titik koordinat yang sudah ditentukan, dan daerah penangkapan ikan dengan luas 1.019.78 km2 antara Pulau Lepar dan Pulau Pongok. Puncak musim pemijahan yaitu pada bulan April dan Juli. Pengaturan untuk zona budidaya KJA di perairan yang mengelilingi Pulau Pongok dengan luas 3.474.66 ha atau 34.75 km2 yang setara dengan 16.700 unit KJA (Adibrata et al. 2013), sebelum dikurangi zona pariwisata sebagai bagian dari RTRW Kabupaten Bangka Selatan 2014-2034. Nilai R/C dan PP masing-masing sebesar 1.17 dan 2.61 tahun dengan modal awal sebesar Rp 116.500.000.00/kapal nelayan mencerminkan bahwa jenis usaha ini menguntungkan dan layak untuk dilaksanakan, komponen biaya secara berurut dari yang terbesar adalah komponen tenaga kerja, penyusutan alat habis pakai terutama alat tangkap bubu, bahan bakar solar, dan ransum. Pengaturan zona perlindungan dapat menurunkan pendapatan nelayan tetapi masih di atas upah minimum provinsi (Rp 2.534.673.00) yaitu upah untuk juragan sebesar Rp 5.094.000.00/orang/bulan dan ABK sebesar Rp 2.547.000.00/orang/bulan. Di lokasi penelitian terdapat peluang bisnis dari biomassa ikan kerapu sunu sekitar 28.452 kg/tahun atau Rp 2.911.044.000.00/tahun. Usaha penangkapan sebaiknya mempertahankan armada yang ada (12 armada kapal) dan tidak dilakukan penambahan armada karena sudah optimal. Penambahan armada kapal dapat dilakukan tetapi kawasan tangkapan sebaiknya diperluas pada wilayah yang lebih jauh dengan gross tonase (GT) kapal yang lebih besar dan daya jelajah kapal nelayan yang lebih luas. Keterpaduan secara spasial tercermin dari upaya menempatkan lokasi untuk zona perlindungan, daerah penangkapan ikan, dan zona budidaya agar tidak tumpang tindih dan mencegah potensi konflik pemanfaatan ruang dengan mengacu pada kajian ilmiah untuk mencapai visi pengelolaan perikanan kerapu berkelanjutan. Peran kelembagaan sangat menentukan jika seluruh stakeholder memiliki persepsi yang sama mengenai pengelolaan perikanan kerapu yang berkelanjutan. Peran pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, nelayan, dan stakeholder lainnya harus bekerjasama untuk mewujudkan keberlanjutan dalam tinjauan ekologis, sosial, dan ekonomi. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/95968 |
| Appears in Collections: | DT - Fisheries |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2018sad.pdf Restricted Access | 43.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.