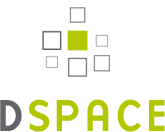Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/92418| Title: | Pengembangan Gamal (Gliricidia sepium) sebagai Kayu Energi di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. |
| Authors: | Nurmansyah, Ali Hidayati, Rini Winasa, I Wayan Hutapea, Dedi |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu daerah yang mengalami kekurangan energi listrik, ditandai dengan 32 desa dari 144 desa sudah mendapat aliran listrik dengan rasio elektrifikasi 59,2%. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hanya 385.033 rumah tangga dari 988.900 rumah tangga yang mendapat layanan listrik dari PLN. Sisanya mendapatkan sumber penerangan dari listrik non PLN, petromax, lilin atau obor, dan dari sumber energi lainnya. Kebutuhan pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sebesar 2,8 GW, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan listrik secara umum, PLN harus menyediakan pembangkit listrik dengan kapasitas 71,6 GW. Gamal (Gliricidia sepium) merupakan tanaman pionir yang dapat menghasilkan sumber kayu api yang baik, terbakar perlahan dan menghasilkan sedikit asap dengan nilai kalori sebesar 4.900 kkal/kg. Kayu gamal berpotensi sebagai bahan baku pembangkit listrik alternatif dari sumber energi terbarukan, yang dapat dikembangkan di Kabupaten Manggarai, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Hal tersebut menjadi inspirasi peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi gamal sebagai bahan baku pembangkit listrik tenaga biomassa, menganalisis skema pemenuhan kebutuhan bahan baku, dan menganalisis kelayakan usaha pengembangan gamal. Penelitian dilakukan dengan metode survei pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan kuisoner dan wawancara. Pengambilan sampel secara purposive sampling pada responden sejumlah 30 orang petani penggarap lahan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dan sintesis kuantitatif untuk mengidentifikasi lahan kritis dengan tools ArcGIS Ver.10.1. Hasil identifikasi lahan kritis digunakan untuk menghitung potensi gamal sebagai bahan baku pembangkit listrik berdasarkan jarak tanam sesuai tingkat kritis lahan menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/Menhut-II/2014. Analisis skema pengembangan gamal berdasarkan perhitungan kebutuhan bahan baku pembangkit listrik sebesar 1 MW dan kebutuhan lahan budidaya dengan pertimbangan jarak optimal dari lokasi pembangkit menggunakan garis lurus sepanjang 2,5 km. Analisis kelayakan usaha untuk budidaya gamal secara monokultur dan agroforestri meliputi nilai NPV (Net Present Value), B/C ratio (Benefit Cost Ratio) atau IRR (Internal Rate of Return), dan suku bunga diskonto (discount rate) sebesar 5%. Hasil penelitian menunjukan lahan yang tersedia di Kabupaten Manggarai Timur seluas 187.462 ha, dengan kategori sangat kritis 1.887 ha, kritis 118.415 ha, agak kritis 41.225 ha, dan potensial kritis 25.905 ha. Secara keseluruhan apabila dikembangkan untuk gamal, potensi energi listrik yang dapat dihasilkan dari ketersediaan lahan sebesar 18,90 MW. Berdasarkan kategori kekritisan lahan, potensi energi listrik pada lahan sangat kritis sebesar 1,8 MW, kritis 13,93 MW, agak kritis sebesar 2,67 MW dan potensial kritis sebesar 0,84 MW. Pembangkit listrik kapasitas 1 MW memerlukan bahan baku sebesar 10.572 ton/tahun yang dapat dipenuhi dari 2.590 ha lahan sangat kritis dan lahan kritis seluas 10.360 ha. Pemilihan lokasi budidaya gamal perlu mempertimbangkan, antara lain: lahan budidaya dekat dengan lokasi pembangkit, meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, ketersediaan tenaga kerja, tersedianya fasilitas jalan angkut bahan baku dan memiliki kriteria lahan sangat kritis atau kritis. Skema pengembangan berdasarkan kedekatan lokasi, yaitu prioritas pertama pada lahan kritis berada pada kisaran 0-2,5 km seluas 1.540 ha; 25-5 km seluas 3.807 ha; dan jarak 5,00-7,50 seluas 5.383 ha, sedangkan lahan sangat kritis seluas 1.887 ha terletak pada jarak 25-35 km merupakan prioritas kedua. Kelayakan usaha finansial untuk budidaya gamal monokultur dilakukan pada lahan sangat kritis, dengan asumsi 10.000 pohon setara 10,5 ton, harga jual kayu Rp 300.000/ton, jangka waktu investasi 10 tahun, dan bunga bank untuk kredit hutan tanaman rakyat 5% per tahun. Modal budidaya monokultur secara keseluruhan sebesar Rp 18.391.000 dan penerimaan sebesar Rp 28.350.000. Untuk budidaya agroforestri gamal dengan kopi dilakukan pada kriteria lahan kritis, dengan asumsi jumlah gamal 2.500 pohon setara 2,63 ton dan kopi 2.500 pohon setara 600 kg, harga jual Rp 20.000/kg, jangka waktu investasi 10 tahun, dan bunga bank untuk kredit hutan tanaman rakyat 5% per tahun. Modal budidaya agroforestri secara keseluruhan sebesar Rp 71.995.750 dan penerimaan sebesar Rp 115.087.500. Secara umum budidaya gamal memberikan nilai positif, baik dilakukan secara monokultur atau sistem agroforestri dengan tanaman kopi. Budidaya sistem agroforestri antara gamal dengan kopi memberikan keuntungan lebih besar dibandingkan budidaya gamal secara monokultur. NVP agroforestri sebesar 52.757.800 berbanding 7.410.613 dengan monokultur gamal. B/C ratio agroforestri sebesar 0,25%, sedangkan B/C ratio monokultur gamal sebesar 14%. Hal ini berlaku untuk tingkat pengembalian modal 7 Tahun 1 Bulan bagi budidaya monokultur gamal dan 6 Tahun 1 Bulan untuk budidaya gamal agroforestri. Hal ini sejalan dengan IRR, yaitu budidaya monokultur gamal sebesar 51% dan dengan budidaya gamal agroforestri sebesar 68%. Berdasarkan hasil analisis kelayakan ini, usaha budidaya gamal untuk menghasilkan kayu sebagai bahan baku pembangkit listrik layak untuk dikembangkan. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/92418 |
| Appears in Collections: | MT - Agriculture |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2018dhu.pdf Restricted Access | 17.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.