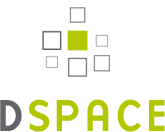Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/69903| Title: | Adaptasi Perubahan Iklim dan Resiliensi Komunitas Desa Nelayan: Studi Kasus di Kawasan Pesisir Utara Pulau Ambon, Maluku |
| Authors: | Kolopaking, Lala M. Adiwibowo, Soeryo Pranowo, M. Bambang Subair |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | IPB (Bogor Agricultural University) |
| Abstract: | Dari 712.479,69 km2 total luas wilayah Maluku, 93 persen lebih (666.139,85 km2) terdiri atas lautan. Selain itu, lebih dari 83 persen desa berada di daerah pantai sehingga aktivitas masyarakat pedesaan sebagian besar dilakukan di daerah pesisir dan laut. Perairan yang begitu luas mengindikasikan bahwa laut memiliki peran yang vital bagi kehidupan, sehingga dapat dikatakan bahwa laut merupakan ―ladang kehidupan‖ bagi penduduk di Maluku. Karakteristik geografis dan penduduk yang terkait dengan pesisir dan laut membuat Maluku secara teori rentan terhadap dampak perubahan iklim. Di Indonesia, penelitian serta bukti-bukti kredibel tentang dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat pedesaan khususnya nelayan perikanan tangkap masih kurang. Selain itu, cara paling umum dalam mengkaji perubahan iklim selama ini adalah melalui pengamatan meteorologis. Dampak iklim seringkali didasarkan pada simulasi model-kenaikan permukaan air laut yang diarahkan sebagai adaptasi biofisik terhadap intrusi air laut ke daratan. Model simulasi seperti itu seringkali non-sensitive terhadap faktor-faktor sosial ekonomi yang sering ditemukan pada kasus studi-studi kualitatif. Penelitian ini merupakan kajian kerentanan dan resiliensi dengan cara yang relatif baru menggunakan metode kualitatif, dilaksanakan dengan pendekatan eksplorasi, bukannya mengenalkan. Informasi yang digali dari masyarakat adalah pandangan (pemahaman) masyarakat terhadap kondisi iklim dan perubahannya yang berlaku di lokalitas wilayah penelitian, pandangan yang dapat saja berbeda dengan pandangan ilmuwan. Tujuan umum dari penelitian ini adalah membuat sintesis berkaitan dengan pemahaman nelayan tentang perubahan iklim, strategi adaptasi, serta proses pengambilan keputusan adaptasi sebagai bahan untuk merumuskan formulasi kebijakan advokasi perubahan iklim berbasis evidensi pedesaan nelayan pada kawasan pesisir. Tujuan penelitian lebih rinci dirumuskan sebagai berikut: (1) Mengidentifikasi kerentanan komunitas nelayan melalui penilaian paparan, kepekaan, dan kemampuan adaptasi, (2) Menganalisis strategi adaptasi dalam mengurangi kerentanan dan meningkatkan resiliensi komunitas terhadap dampak perubahan iklim dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya, dan (3) Menganalisis peran pemerintah dan stakeholder lainnya dalam memfasilitasi praktek strategi adaptasi yang dilakukan komunitas nelayan sebagai bahan untuk merumuskan langkah penyusunan kebijakan pembangunan peka iklim. Penelitian dilakukan di kawasan pesisir utara Pulau Ambon yakni pada desa nelayan sentra perikanan komoditas komersial ikan Tuna Asilulu yang ditetapkan secara purposif. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus historis. Predikat ‗historis‘ di sini menekankan bahwa pokok kajian penelitian ini bukan suatu kejadian sosial pada suatu waktu tertentu, melainkan suatu gejala atau proses sosial dalam suatu rentang waktu tertentu. Istilah ‗kasus‘" sendiri memberi pembatasan bahwa proses sosial yang dikaji tidak berada dalam cakupan sejarah non-kontemporer (klasik), melainkan dalam cakupan sejarah kontemporer yang sebagian pelakunya masih hidup. Unit analisis adalah komunitas nelayan di desa Asilulu kecamatan Leihitu kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku dan kelompok sosial yang ada di dalamnya. Jumlah informan yang dipilih sebanyak 16 orang informan yang terdiri dari unsur nelayan anggota komunitas sebanyak 5 orang, pengumpul 3 orang mewakili 3 lembaga pengumpul, unsur pemerintah desa 1 6 orang, dan unsur pemerintah daerah 2 orang, dan unsur pakar 3 orang. Seluruh informan dalam penelitian ini dipilih secara sengaja (purposif) sesuai dengan kebutuhan penelitian, pengetahuan dan pengalaman informan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode hermeunetik dan dialektika yang difokuskan pada konstruksi, rekonstruksi dan elaborasi suatu proses sosial. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik pengamatan berperan serta (participant-observation), Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam secara langsung pada tineliti. Untuk mendukung validitas data yang dikumpulkan, dilakukan pula studi pustaka, terutama terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu serta dokumen-dokumen terkait lainnya. Data yang berasal dari hasil wawancara mendalam, dan observasi yang telah disunting dan ditranskripsi dianalisis menggunakan analisa kualitatif fenomenologi dan strategi analisis data kualitatif-verifikatif yang keduanya dilakukan secara induktif. Selain analisis induktif, digunakan juga analisis deduktif khususnya untuk menilai tingkat kerentanan komunitas terhadap dampak perubahan iklim. Dalam hal ini, terlebih dahulu disusun kriteria-kriteria kerentanan beserta hipotesis-hipotesis berdasarkan literatur yang ada kemudian membandingkannya dengan kondisi eksisting sosial ekonomi budaya komunitas. Nelayan dan semua stakeholder perikanan tangkap di Negeri Asiluli telah menjadi saksi terjadinya pola musim yang berbeda dalam beberapa tahun terakhir. Ada tiga pola angin musim yang dikenal nelayan, yakni musim barat, musim timur, dan musim pancaroba. Saat ini nelayan kesulitan untuk dapat memprediksi secara tepat kapan pergantian antara satu musim ke musim yang lain. Kalender musim yang menjadi pedoman secara turun temurun prediksinya kebanyakan tidak tepat lagi. Pola angin musim yang tidak sama ini membingungkan nelayan dalam menentukan keputusan pergi melaut. Banyak nelayan yang salah memperhitungkan pola angin musim ketika berangkat ke laut. Angin musim juga terkait dengan jenis ikan apa yang sedang banyak dan lokasinya, apakah ikan ada di tengah laut atau di perairan dangkal. Ketika gelombang dan angin kencang datang tiba-tiba dan nelayan memutuskan untuk tetap melaut, biasanya nelayan kesulitan memancing ikan. Musim ikan mati (panen) mundur atau maju sebulan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengetahuan yang mereka jadikan kekuatan utama dalam menopang nafkah keluarga secara perlahan mulai tidak lagi relevan. Bisa jadi hasil panen ikan melimpah tahun ini tetapi mereka mulai khawatir dengan tahun depan. Tentunya ini berdampak pada keselamatan dari nelayan dan hasil tangkapan ikan yang berarti bahwa nelayan dan keluarganya (dan semua pihak yang terkait dengan sumberdaya pesisir dan laut) terhempas ke dalam kondisi kerentanan, secara ekologis, sosial dan ekonomi. Nelayan tidak mengetahui perdebatan tentang perubahan iklim yang ramai di sisi lain dunia mereka, yang mereka tahu: mereka harus beradaptasi untuk tetap eksis sebagai satu masyarakat. Kerentanan yang dipicu oleh dampak negatif sejauh ini dapat dikurangi oleh adaptasi yang dilakukan. Sampai di sini, komunitas dapat disebut cukup resilien tetapi dengan resiliensi yang terbatas (limited resilience) karena ketergantungan yang masih sangat tinggi pada keramahan sumberdaya alam. Adaptasi yang terlihat sebagai adaptasi reaktif sesungguhnya adalah adaptasi yang direncanakan (plan adaptation) mengingat perubahan iklim adalah fenomena yang terjadi dalam proses yang sangat lama dan bertahap. Faktor yang sangat penting dalam menciptakan keadaan keadaan yang resilien adalah peran besar lembaga-lembaga lokal yang menfasilitasi tindakan adaptasi yang dilakukan. Kesuksesan adaptasi perubahan iklim ditentukan oleh keberadaan dan keberfungsian lembaga lokal ini. Semakin kuat dan mengakar lembaga lokal maka semakin besar peluang kesuksesan komunitas melakukan adaptasi perubahan iklim. Sebaliknya, semakin lemah dan ―terasing‖ maka semakin kecil kemungkinan berhasil melakukan adaptasi. Lebih jauh dapat dikatakan bahwa adaptasi perubahan iklim oleh komunitas, karenanya, lebih efektif dibanding adaptasi yang dikelola oleh pemerintah. Pandangan ini mensyaratkan bahwa dalam penyusunan kerangka kebijakan adaptasi, komunitaslah yang harus menjadi basis. Pada intinya, keseluruhan strategi itu terjadi dan terus bergerak maju karena salah satunya dan yang utama, adanya dukungan kelembagaan lokal yang tumbuh dari komunitas mereka sendiri. Kelembagaan ini adalah jaringan sosial nelayan – pedagang pengumpul yang menjadi pola sistem nafkah nelayan Tuna di Asilulu saat ini. Masyarakat setempat menjadikan jaringan sosial yang ada sebagai sumber dukungan sosial. Studi ini mengidentifikasi setidaknya terdapat dua dukungan sosial yang diperoleh: dukungan instrument dalam bentuk bantuan langsung, bantuan kredit kepemilikan alat tangkap dan bantuan pinjaman biaya operasional penangkapan; dan dukungan informasi berupa informasi wilayah konsentrasi ikan, telah mulainya musim ikan mati, jenis umpan yang sedang disukai ikan Tuna, informasi cuaca dan badai serta informasi lainnya yang terkait dengan sistem nafkah nelayan. Kedua dukungan sosial itu diprakarsai, dikembangan dan dikendalikan oleh pedagang pengumpul, patron yang dalam konteks mereka menjadi ―bapak‖ yang mengayomi. Tentu saja dibutuhkan penelitian lagi untuk mengungkap dinamika rasionalitas pada hubungan keduanya untuk mengungkap kebenaran yang mungkin tersembunyi. Secara umum, bentuk lembaga lokal membentuk efek bahaya iklim dalam tiga hal penting: mereka menentukan bagaimana rumah tangga dipengaruhi oleh dampak iklim; mereka membentuk kemampuan rumah tangga untuk menanggapi dampak iklim dan mengejar praktek adaptasi yang berbeda, dan mereka memediasi aliran eksternal intervensi dalam konteks adaptasi. Nilai kegigihan, ketekunan dan sikap budaya sebagai penduduk pesisir kepulauan dan nelayan ditambah dukungan kelembagaan menjadi ―modal‖ yang menguatkan kemampuan adaptasi nelayan dalam beradaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim. Kemampuan adaptasi yang kuat membawa masyarakat nelayan pada kondisi yang resilien, dan inilah yang disebut sebagai resiliensi sosial nelayan. Meskipun masih perlu kajian lebih lanjut untuk memperhadapkan kemampuan adaptasi itu dengan kerentanan yang diakibatkan oleh perubahan iklim karena asumsi dasar dari studi ini adalah bahwa tingkat keparahan dan krisis yang diakibatkan oleh dua sisi: kerentanan dan resiliensi sosial. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/69903 |
| Appears in Collections: | DT - Human Ecology |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2014sub.pdf Restricted Access | Fulltext | 68.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.