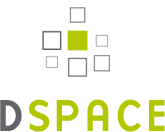Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/118582| Title: | Memudarnya “Bari” Dan Kelembagaan “Mabari” ( Studi Pada Komunitas Petani Kelapa di Dua Desa di Kabupaten Halmahera Barat) |
| Authors: | Kolopaking, Lala M Sumarti, Titik Ali, Muhammad Syarif A |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | Bogor Argicultural University (IPB) |
| Abstract: | Bari merupakan nilai dasar kelembagaan masyarakat yang dikenal sebagai Mabari, yang keberadaan kelembagaan tersebut sebagai pranata sosial dengan dasar proses sosial yang bersifat assosiatif di Kabupaten Halmahera Barat. Gejala melemahnya kohesifitas sosial diperkirakan berkaitan dengan melemahnya bari atau nilai-nilai sosial yang mengatur pola dan semangat hidup yang di dasarkan pada kepercayan, keterbukaan, saling peduli, saling menghargai, dan saling menolong diantara anggota kelompok masyarakat. Padahal mabari sebagai kelembagaan lokal dapat didayagunakan untuk menjaga solidaritas masyarakat dalam pembangunan. Bahkan, ada pandangan, bahwa pemanfaatan kelembagaan-kelembagaan lokal tersebut dapat dijadikan sarana efektif untuk percepatan pembangunan pedesaan di Kabupaten Halmahera Barat. Dengan dasar pemikiran, bahwa nilai-nilai budaya dan pengetahuan lokal yang telah lama tertanam dalam masyarakat menjadi modal yang berharga pembangunan. Berdasarkan perkembangan itu penting dilakukan kajian keberadaan dan perkembangan bari dan mabari. Penelitian berlokasi di Desa Susupu dan Desa Lako Akelamo Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat, dengan pendekatan penelitian adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan metode pengamatan terlibat dan wawancara mendalam. Sementara untuk menyalami kultur masyarakat dan melibatkan diri sebagai bagian dari masyarakat supaya mengenal lebih jauh mengenai kehidupan masyarakat di daerah yang diteliti, maka peneliti menggunakan metode pengamatan berpartisipasi. Dalam menganalisis data berpedoman pada pandangan Milles dan Huberman (1992) dengan analisis kualitatif yang terdiri dari reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi. Untuk mengetahui mengetahui situasi sosial komunitas di dua Desa, harus menuju kota Jailolo sebagai pintu gerbang Halmahera, sekaligus pintu masuk menuju desa Susupu dan Lako Akelamo. Menuju Desa Susupu dan Lako akelamo di tempuh dengan kendaraan dalam waktu 30 menit. Susupu adalah Ibu Kota kecamatan Sahu, sementara Desa Lako Akelamo adalah hasil pemekaran desa Susupu pada tahun 1985. Dari sisi administrasi pemerintahan, desa Susupu dan Desa Lako akelamo memiliki wilayah otonomnya masing-masing, namun kedua Desa memiliki akar historis dan kultur yang sama. Kedua Desa memiliki perbedaan soa. Soa adalah bentuk stratifikasi sosial yang di dasarkan pada hubungan feodal yang diberikan berdasarkan status dan peran melalui hubungan keturunan/kekerabatan. Masyarakat dua Desa mengenal dengan empat soa data “soa raha” yaitu, soa sangaji, soa siyodi, soa talai dan soa padisua. Desa susupu lebih di dominasi oleh stratifikasi soa sangaji, karena terdapat kerabat dan keturunan sultan, sementara desa Lako Akelamo lebih di dominasi oleh soa siyodi, yang merupakan komunitas pengayom dan pelestari adat istiadat. Dengan adanya kemajuan dan perubahan sosial telah menggeser model stratifikasi sosial berdasarkan feodal menjadi model kalsifikasi sosial berdasarkan profesi. Hilangnya stratifikasi feodal, berpengaruh terhadap nilai bari dan kelembagaan mabari. Bari dan kelembagaan mabari pada stratifikasi sosial feodal begitu eksis karena penghormatan terhadap tetua adat (tokoh adat), tokoh agama. Saat ini penghormatan tokoh adat telah bergeser kepada penghormatan sesorang atas kekuasaan dan jabatan seperti PNS, TNI, pengusaha, dokter. iv Pembangunan membawa sertakan teknologi memberikan dampak perubahan terhadap komunitas di dua Desa. Bentuk perubahan terlihat pada organisasi pertanian masyarakat kedua Desa. Kehadiran sepeda motor, perahu motor dan listrik masuk desa,menyebabkan tradisi fala adat gura (rumah adat kebun) menjadi hilang. Hilangnya fala adat gura sangat berpengaruh terhadap nilai bari dan mabari, karena fala adat gura bukan saja diperuntukan sebagai rumah inap para petani, namun berfungsi sebagai tempat bermusyawarah, penyelesaian konflik antar petani, serta merencanakan kegiatan-kegiatan mabari. Hilangnya fala adat gura, semakin menguatkan individualitas para petani dan “alur kekerabatan” semakin kabur. Hasil penelitian menemukan, bahwa bari sebagai nilai dasar berkembangannya kelembagaan mabari masih menjadi ketetapan sosial dari tatanan kehidupan masyarakat pedesaan di Kabupaten Halmahera Barat, khususnya komunitas perkebunan kelapa rakyat. Meskipun, intensitas kekuatan mengikat dan pelembagaan nilai bari dan keaktifan bentuk pelaksanaan mabari beragam antar desa. Mabari pada proses produksi petani kelapa masih dapat ditemukan di komunitas petani kelapa mulai dari pembukaan lahan, pembibitan, pemeliharaan, pembersihan, hingga pemanenan di lakukan dengan dinstrumen ritual. Terdapat enam tahap pembukaan dengan tradisi bari, yaitu tola gumi manyigu , madoti, majongo, “mabaca” dan masagu. Terdapat istilah oro wange (ambil hari) dalam tradisi bari di dua desa. Oro wange adalah model pertukaran kerja yang diberlakukan pada pekerjaan yang sama. Oro wange mencirikan nilai-nilai “bari”, namun perbedaannya adalah bari melibatkan semua pekerja, tanpa mengenal batasan kerja yang harus dikerjakan, sementara oro wange hanya ada dan terdapat pada pekerjaan yang sama. Disisi lain, terdapat perbedaan pada kegiatan mabari pada pola produksi kelapa, antara Desa Susupu dan Lako Akelamo. Mabari di Desa Susupu menanggung semua pembiayaan konsumsi (makanan minum dll) para anggota bari, sementara didesa Lako Akelamo para anggota mabari datang dengan membawa makanannya masing-masing untuk melaksanakan kegiatan mabari. Pada sisi lain, tradisi mencuri bibit (tori gura) juga ikut mewarnai aktfitas mabari. Tradisi ini dengan tujuan memberikan surprise bagi pemilik lahan atau orang yang sedang melakukan kegiatan menanam. Teknologi dan pengetahuan baru telah menggeser ukuran mengenai efisiensi produksi. Bila di masa lalu, aktivitas mabari dianggap sebagai cara untuk berproduksi dengan maksimal, kini persepsi itu mulai berubah. Aktifitas panen para petani tak lagi mengandalkan kerja bersama melainkan membayar tenaga kerja untuk mengambil kelapa. Perubahan tersebut karena adanya introduksi unsur materi dalam masyarakat. Pengaruh unsur materi dalam hal ini terutama sekali adalah cash money (uang), unsur uang sebagai bentuk kompensasi atas kerja yang dilaksanakannya. Spesialisasi pekerjaan pun muncul karena kini orang dapat menghasilkan uang dengan spesialisasi kerja yang di milikinya. Muncul variasi pekerjaan, kini warga desa tak hanya sebagai petani, melainkan juga mereka yang mengandalkan hidup dari keterampilan sebagai tukang, atau sebagai pemanjat pohon kelapa bayaran, jenis pekerjaan yang di masa lalu semua bisa mengerjakan secara mabari. Cara produksi pun mulai berubah, petani lebih memilih panen dengan menyewa tukang panjat, membersihkan kebun dengan menyewa alat pemotong rumput, dan lain-lain. Cara orang mendirikan rumah telah berubah, mereka harus membayar tukang A, tukang untuk B, dan lain-lain. Konsekwensinya adalah biaya meningkat untuk produksi, biaya juga meningkat untuk mendirikan rumah. Perubahan situasi pasar, dengan jatuhnya harga kopra, ditambah meningkatnya unsur-unsur dalam pembiayaan produksi akibat munculnya efisiensi yang berideologikan cash money menyebabkan masyarakat tertekan oleh situasi ekonomi yang memiskinkan mereka. Itu menyebabkan mereka melakukan cara-cara survival dengan memvariasi aktivitas kerja mereka. Mereka adalah petani merangkap tukang ojek, merangkap yang lain-lain, agar mendapatkan tambahan penghasilan. v Modernitas ternyata harus dibayar mahal oleh masyarakat. Itu sebabnya sikap masyarakat pun beragam terhadap perubahan. Mereka yang menerima perubahan dengan setia mengadopsi masuknya unsur-unsur perubahan termasuk teknologi pertanian, teknologi kesehatan, dan lain-lain. Pada sisi lain, masyarakat mengalami penurunan tingkat partisipasi sosial, partisipasi kesukarelaan bergeser sedikit demi sedikit. Partisipasi dalam program pemerintah diberikan sejauh program tersebut dapat diakses dan memberikan keuntungan. Ini rational choice, pilihan rasional untuk mendapatkan keuntungan atau kemanfaatan dalam pembangunan. Solidaritas sosial bergeser dengan orientasi unsur materi.Sementara mereka yang bertahan, sebagaimana ditunjukkan oleh masyarakat Lako Akelamo, berada pada akses yang lebih terbatas terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Mereka adalah masyarakat yang homogenitasnya tinggi, sama-sama orang Lako Akelamo, sama-sama petani kelapa. Hampir tak ada variasi. Di sana tokoh lokal juga masih kuat pengaruhnya. Kesamaan-kesamaan ini menjaga eksistensi mabari dalam kehidupan masyarakatnya. Kemampuan masyarakat dalam mempertahankan pola hubungan sosialnya menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kapasitas membangun mekanisme sosialnya sendiri yang itunjukkan oleh kuatnya masyarakat mengatur dan membentuk kelembagaan penyelesaian konflik produksi maupun konflik sosial pada umumnya. Masyarakat menunjukkan dirinya sebagai aktor yang memiliki kemampuan tidak tereduksi oleh hukum negara. Ini terlihat benar ketika konflik perebutan lahan di antara mereka, mereka memilih menyelesaikannya dalam ritual sasi, dari pada menyerahkan penyelesaian dengan jalur hukum negara. Pembangunan merupakan unsur utama yang membawa serta gejala perubahan sosial masyarakat. Infrastruktur, birokrasi, teknologi, pengetahuan baru dan orientasi uang adalah intrumen yang melekat padanya. Perubahan pada eksistensi kelembagaan sosial mabari adalah gejala sosial di masyarakat merepresentasikan perubahan sosial yang tengah berlangsung. Masyarakat dua desa itu menunjukkan dua respon, menerima dan hanyut dalam gejala perubahan dengan menanggung resiko memudarnya kohesi sosial, dan di pihak lain menunjukkan gejala resistensi terhadap unsur-unsur perubahan tersebut. Mereka yang menolaknya menunjukkan resistensi terhadap unsur-unsur modern, mereka memilih dukun, mereka memilih tetap menjalankan bari dalam proses produksinya. Sementara mereka yang terbawa arus perubahan ditunjukkan oleh masyarakat Desa Susupu yang memperkecil kelembagaan mabari hanya dalam aktivitas pengolahan kopra pasca panen, hingga pun menghilangkan unsur kebersamaan lainnya seperti dalam pembangunan rumah yang harus mengganti unsur kerja sukarela menjadi lebih komersial. Kelembagaan mabari merupakan simpul atau mewakili gambaran masyarakat di pedesaan yang hidup didasarkan pada pola kerjasama, tolong menolong, saling peduli, memiliki nilai, norma dan kepercayaan. Bari sebagai nilai sosial budaya dan pengetahuan lokal yang telah lama tertanam pada masyarakat Halmahera Barat pada umumnya, diharapkan senantiasa terpelihara dan berkembang menjadi modal yang bernilai harganya dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, semestinya kebijakan pemerintah dalam bentuk implementasi program pembangunan di desa lebih intensif memanfaatkan mabari sebagai kelembagaan lokal yang ada dimasyarakat. Melembagakan nilai-nilai bari dalam setiap kebijakan dan program pemerintah daerah merupakan suatu langkah startegis untuk memberdayakan masyarakat. Internalisasi nilai-nilai bari pada setiap aspek kehidupan merupakan wujud dari upaya untuk memlihara, mempertahankan dan memperkuat kelembagaan mabari |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/118582 |
| Appears in Collections: | MT - Human Ecology |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 2010msa.pdf Restricted Access | Fulltext | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.