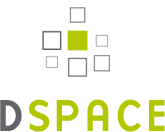Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/107050| Title: | Model Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Barat Secara Berkelanjutan |
| Other Titles: | Capture Fisheries Management Model and Its Impact on Community Welfare in West Java Province in a Sustainable Way |
| Authors: | Fauzi, Akhmad Adrianto, Luky Suwandi, Ruddy Wijayanto, Donny Orlando |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Provinsi Jawa Barat adalah pemegang mandat pengelola sumber daya perikanan laut di wilayahnya. Area pengelolaan perikanan laut yang termasuk ke Provinsi Jawa Barat adalah di Laut Jawa (WPP-712) dan di Samudra Hindia (WPP-573). Kondisi ini membuat Provinsi Jawa Barat menjadi unik karena menjadi pengelola tunggal untuk dua wilayah pengelolaan perikanan yang berbeda secara geografis. Hasil perikanan laut republik Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar 6.424.114,151 ton, dengan Provinsi Jawa Barat menghasilkan produksi sebesar 231.453,478 ton, menempatkannya pada urutan ke – 9 produsen perikanan laut nasional. Secara regional, sektor perikanan menyumbang sebesar 0,97% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat, dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,17%.
Produksi perikanan laut di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kecenderungan yang meningkat, baik yang berasal dari WPP-712 maupun yang berasal dari WPP-573. Rasio antara jumlah hasil tangkapan dengan upaya penangkapan (Catch Per Unit Effort/CPUE) menunjukkan kecenderungan yang menurun di WPP-712. Hal sebaliknya terjadi di WPP-573, dimana CPUE memiliki kecenderungan meningkat. Penurunan CPUE mengindikasikan bahwa meskipun jumlah hasil tangkapan meningkat, upaya yang harus dikeluarkan pun meningkat, yang berarti bahwa ikan semakin sulit untuk ditangkap. Kejadian ini menjadi suatu masalah karena dapat mengganggu tujuan pengelolaan perikanan.
Rumusan masalah disusun sebagai sintesis dari masalah yang teridentifikasi, yaitu terjadinya disparitas antar wilayah pengelolaan perikanan yang mengakibatkan ketidakseimbangan efisiensi, optimasi, dan keseimbangan antar pemangku kepentingan. Masalah ini dipecahkan melalui suatu model terintegrasi pengelolaan perikanan laut. Model terintegrasi ini terdiri dari serangkaian langkah-langkah berupa kajian kapasitas terpasang perikanan laut, kajian keseimbangan bioekonomi perikanan laut, kajian dinamika sistem perikanan laut, dan kajian pemangku kepentingan perikanan laut.
Berdasarkan uraian di atas, jawaban dari hipotesis penelitian, yaitu terjadinya disparitas perikanan laut di Provinsi Jawa Barat antara WPP-712 dengan WPP-573, yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam perspektif efisiensi, optimasi, dan keseimbangan antar pemangku kepentingan, adalah sebagai berikut. Perbedaan antara WPP-712 dengan WPP-573 terjadi pada variabel yang mempengaruhi produksi. Produksi perikanan dipengaruhi oleh jumlah armada penangkapan dan tenaga kerja di WPP-712; sedangkan di WPP-573 produksi dipengaruhi oleh upaya penangkapan. Dari perspektif efisiensi, terdapat dua wilayah di WPP-712, yaitu Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi yang mengalami increasing return to scale; sedangkan di WPP-573 hanya ada satu, yaitu Kabupaten Cianjur. Dari sisi produktivitas, perikanan laut baik di WPP-712 maupun di WPP-573 cenderung stagnan. Hal ini tercermin dari parameter Indeks Produktivitas Malmquist yang mengukur perubahan Total Factor Productivity yang nilainya mendekati satu. Selain itu, produktivitas di kedua WPP dipengaruhi oleh efisiensi teknis dan efisiensi skala. Kondisi ini menunjukkan proses produksi berlangsung sesuai kemampuannya.
Jawaban hipotesis penelitian dari sisi bioekonomi adalah sebagai berikut. Nilai kemampuan penangkapan adalah setara di kedua WPP; cerminan dari armada perikanan yang didominasi kapal berukuran 5 GT atau lebih kecil. Nilai daya dukung lingkungan adalah lebih besar di WPP-712 daripada di WPP-573; cerminan dari kondisi fisik perairan yang merupakan laut pedalaman (WPP-712) dan samudra terbuka (WPP-573). Kondisi stok sumber daya ikan
baik di WPP-712 maupun di WPP-573 berstatus tereksploitasi penuh atau tereksploitasi lebih untuk seluruh kelompok spesies ikan. Besaran biaya melaut di WPP-712 relatif lebih kecil daripada di WPP-573; gambaran dari risiko yang harus dihadapi dalam melakukan proses produksi. Perbedaan risiko yang harus dihadapi antara ketika melaut di laut pedalaman dengan melaut di laut lepas terlihat dari nilai discount rate yang optimal. Rente ekonomi berupa rata-rata surplus produsen diperoleh pada nilai discount rate optimal 5% di WPP-712 dan 10% di WPP-573. Nilai optimal rente ekonomi berupa pendapatan bersih lestari diperoleh pada kondisi kepemilikan tunggal di WPP-712 dan WPP-573. Perbedaan atribut perikanan laut terjadi pada variabel pendapatan marginal di mana nilainya negatif di WPP-573 untuk semua kelompok spesies ikan, namun di WPP-712 bernilai negatif hanya untuk kelompok spesies pelagis.
Rekomendasi kebijakan dapat disusun dari hasil uraian tersebut sebelumnya sebagai berikut. Secara umum diperlukan kebijakan yang spesifik untuk masing-masing wilayah pengelolaan perikanan. Model terintegrasi yang disusun ini dapat diterapkan dalam asesmen perikanan laut. Model ini terdiri dari analisis kapasitas terpasang perikanan laut, analisis kapasitas sasaran perikanan laut, simulasi dinamik perikanan laut, dan analisis pemangku kepentingan berikut berbagai alat analisisnya. Berdasarkan hasil analisis efisiensi, pembangunan dan pengelolaan perikanan laut dapat difokuskan pada peningkatan penggunaan teknologi penangkapan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, dan efisiensi birokrasi. Efisiensi birokrasi dapat ditempuh dengan perbaikan kualitas layanan publik, melalui pemenuhan prosedur operasi standar yang berlaku. Urgensi dari peningkatan teknologi berada di WPP-573. Analisis menunjukkan bahwa peningkatan jumlah armada berpengaruh negatif terhadap produksi. Ini berkorelasi dengan ukuran armada penangkapan yang kapasitasnya kecil. Dengan meningkatkan kapasitas armada penangkapan, diharapkan pengaruhnya terhadap produksi menjadi positif. Lokasi pembangunan dapat diprioritaskan pada daerah yang mengalami increasing return to scale/irs baik di WPP-712 maupun di WPP-573. Upaya penangkapan ikan agar dikendalikan pada kondisi saat ini atas pertimbangan penyediaan lapangan pekerjaan. Perluasan penyediaan lapangan pekerjaan dapat dilakukan dengan mengusahakan adanya nilai tambah dari hasil perikanan. Kemudian, dengan adanya bisnis dari nilai tambah hasil perikanan diharapkan adanya investasi yang mengalir masuk. Secara operasional, keterbatasan kewenangan antara berbagai tingkat administrasi pemerintahan dapat diatasi dengan mengoptimalkan aplikasi dari peraturan perundangan yang berlaku. Provinsi Jawa Barat adalah pemegang mandat pengelola sumber daya perikanan laut di wilayahnya. Area pengelolaan perikanan laut yang termasuk ke Provinsi Jawa Barat adalah di Laut Jawa (WPP-712) dan di Samudra Hindia (WPP-573). Kondisi ini membuat Provinsi Jawa Barat menjadi unik karena menjadi pengelola tunggal untuk dua wilayah pengelolaan perikanan yang berbeda secara geografis. Hasil perikanan laut republik Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar 6.424.114,151 ton, dengan Provinsi Jawa Barat menghasilkan produksi sebesar 231.453,478 ton, menempatkannya pada urutan ke – 9 produsen perikanan laut nasional. Secara regional, sektor perikanan menyumbang sebesar 0,97% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat, dan mengalami pertumbuhan sebesar 3,17%. Produksi perikanan laut di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kecenderungan yang meningkat, baik yang berasal dari WPP-712 maupun yang berasal dari WPP-573. Rasio antara jumlah hasil tangkapan dengan upaya penangkapan (Catch Per Unit Effort/CPUE) menunjukkan kecenderungan yang menurun di WPP-712. Hal sebaliknya terjadi di WPP-573, dimana CPUE memiliki kecenderungan meningkat. Penurunan CPUE mengindikasikan bahwa meskipun jumlah hasil tangkapan meningkat, upaya yang harus dikeluarkan pun meningkat, yang berarti bahwa ikan semakin sulit untuk ditangkap. Kejadian ini menjadi suatu masalah karena dapat mengganggu tujuan pengelolaan perikanan. Rumusan masalah disusun sebagai sintesis dari masalah yang teridentifikasi, yaitu terjadinya disparitas antar wilayah pengelolaan perikanan yang mengakibatkan ketidakseimbangan efisiensi, optimasi, dan keseimbangan antar pemangku kepentingan. Masalah ini dipecahkan melalui suatu model terintegrasi pengelolaan perikanan laut. Model terintegrasi ini terdiri dari serangkaian langkah-langkah berupa kajian kapasitas terpasang perikanan laut, kajian keseimbangan bioekonomi perikanan laut, kajian dinamika sistem perikanan laut, dan kajian pemangku kepentingan perikanan laut. Berdasarkan uraian di atas, jawaban dari hipotesis penelitian, yaitu terjadinya disparitas perikanan laut di Provinsi Jawa Barat antara WPP-712 dengan WPP-573, yang mengakibatkan ketidakseimbangan dalam perspektif efisiensi, optimasi, dan keseimbangan antar pemangku kepentingan, adalah sebagai berikut. Perbedaan antara WPP-712 dengan WPP-573 terjadi pada variabel yang mempengaruhi produksi. Produksi perikanan dipengaruhi oleh jumlah armada penangkapan dan tenaga kerja di WPP-712; sedangkan di WPP-573 produksi dipengaruhi oleh upaya penangkapan. Dari perspektif efisiensi, terdapat dua wilayah di WPP-712, yaitu Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi yang mengalami increasing return to scale; sedangkan di WPP-573 hanya ada satu, yaitu Kabupaten Cianjur. Dari sisi produktivitas, perikanan laut baik di WPP-712 maupun di WPP-573 cenderung stagnan. Hal ini tercermin dari parameter Indeks Produktivitas Malmquist yang mengukur perubahan Total Factor Productivity yang nilainya mendekati satu. Selain itu, produktivitas di kedua WPP dipengaruhi oleh efisiensi teknis dan efisiensi skala. Kondisi ini menunjukkan proses produksi berlangsung sesuai kemampuannya. Jawaban hipotesis penelitian dari sisi bioekonomi adalah sebagai berikut. Nilai kemampuan penangkapan adalah setara di kedua WPP; cerminan dari armada perikanan yang didominasi kapal berukuran 5 GT atau lebih kecil. Nilai daya dukung lingkungan adalah lebih besar di WPP-712 daripada di WPP-573; cerminan dari kondisi fisik perairan yang merupakan laut pedalaman (WPP-712) dan samudra terbuka (WPP-573). Kondisi stok sumber daya ikan baik di WPP-712 maupun di WPP-573 berstatus tereksploitasi penuh atau tereksploitasi lebih untuk seluruh kelompok spesies ikan. Besaran biaya melaut di WPP-712 relatif lebih kecil daripada di WPP-573; gambaran dari risiko yang harus dihadapi dalam melakukan proses produksi. Perbedaan risiko yang harus dihadapi antara ketika melaut di laut pedalaman dengan melaut di laut lepas terlihat dari nilai discount rate yang optimal. Rente ekonomi berupa rata-rata surplus produsen diperoleh pada nilai discount rate optimal 5% di WPP-712 dan 10% di WPP-573. Nilai optimal rente ekonomi berupa pendapatan bersih lestari diperoleh pada kondisi kepemilikan tunggal di WPP-712 dan WPP-573. Perbedaan atribut perikanan laut terjadi pada variabel pendapatan marginal di mana nilainya negatif di WPP-573 untuk semua kelompok spesies ikan, namun di WPP-712 bernilai negatif hanya untuk kelompok spesies pelagis. Rekomendasi kebijakan dapat disusun dari hasil uraian tersebut sebelumnya sebagai berikut. Secara umum diperlukan kebijakan yang spesifik untuk masing-masing wilayah pengelolaan perikanan. Model terintegrasi yang disusun ini dapat diterapkan dalam asesmen perikanan laut. Model ini terdiri dari analisis kapasitas terpasang perikanan laut, analisis kapasitas sasaran perikanan laut, simulasi dinamik perikanan laut, dan analisis pemangku kepentingan berikut berbagai alat analisisnya. Berdasarkan hasil analisis efisiensi, pembangunan dan pengelolaan perikanan laut dapat difokuskan pada peningkatan penggunaan teknologi penangkapan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur, dan efisiensi birokrasi. Efisiensi birokrasi dapat ditempuh dengan perbaikan kualitas layanan publik, melalui pemenuhan prosedur operasi standar yang berlaku. Urgensi dari peningkatan teknologi berada di WPP-573. Analisis menunjukkan bahwa peningkatan jumlah armada berpengaruh negatif terhadap produksi. Ini berkorelasi dengan ukuran armada penangkapan yang kapasitasnya kecil. Dengan meningkatkan kapasitas armada penangkapan, diharapkan pengaruhnya terhadap produksi menjadi positif. Lokasi pembangunan dapat diprioritaskan pada daerah yang mengalami increasing return to scale/irs baik di WPP-712 maupun di WPP-573. Upaya penangkapan ikan agar dikendalikan pada kondisi saat ini atas pertimbangan penyediaan lapangan pekerjaan. Perluasan penyediaan lapangan pekerjaan dapat dilakukan dengan mengusahakan adanya nilai tambah dari hasil perikanan. Kemudian, dengan adanya bisnis dari nilai tambah hasil perikanan diharapkan adanya investasi yang mengalir masuk. Secara operasional, keterbatasan kewenangan antara berbagai tingkat administrasi pemerintahan dapat diatasi dengan mengoptimalkan aplikasi dari peraturan perundangan yang berlaku. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/107050 |
| Appears in Collections: | DT - Economic and Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cover.pdf Restricted Access | Cover | 458.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
| H462154094_Donny Orlando W.pdf Restricted Access | Fullteks | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Lampiran.pdf Restricted Access | Lampiran | 986.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.