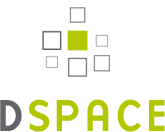Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/106518| Title: | Rekayasa Proses Buang Kapur, Pelumatan dan Penyamakan Kulit Kambing |
| Other Titles: | Engineering of Deliming, Bating, and Tanning Processes of Goat Skin |
| Authors: | Suparno, Ono Indrasti, Nastiti Siswi Hoerudin, Hoerudin Nugraha, Aditya Wahyu |
| Issue Date: | Aug-2020 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Industri penyamakan kulit merupakan bisnis pemanfaatan kulit sebagai hasil samping dari industri daging menjadi kulit samak. Industri penyamakan kulit menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, yakni dengan banyaknya limbah cair dan padat yang terbentuk selama proses konversi kulit samak. Limbah yang dominan terbentuk adalah limbah cair. Limbah tersebut menimbulkan bau busuk di lingkungan industri. Selain itu, Cemaran yang terkandung pada limbah cair tersebut sangatlah tinggi. Bahan yang berpotensi membahayakan lingkungan (toksik dan karsinogenik) juga digunakan pada proses penyamakan kulit. Dan pada umumnya, bahan kimia yang digunakan adalah produk impor dan mempengaruhi biaya produksi kulit samak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merekayasa proses penyamakan kulit ramah lingkungan untuk mendapatkan kulit samak dengan kualitas yang baik. Proses penyamakan kulit terdiri dari proses prasamak, samak, pascasamak dan penyelesaian akhir. Buang kapur merupakan bagian dari proses prasamak, dimana tahap ini dilakukan setelah tahap perendaman dan pengapuran. Amonia merupakan salah satu cemaran yang terbentuk selama tahap buang kapur. Adanya amonia mengganggu pekerja karena memiliki bau yang menyengat. Penggunaan amonium sulfat sebagai deliming agent merupakan penyebab terbentuknya amonia. Untuk menangani permasalahan tersebut telah dilakukan penelitian buang kapur dengan menggunakan asam tartrat. Proses buang kapur dilakukan dalam kondisi asam. Oleh karena itu, tujuan pada tahap ini adalah mengetahui kondisi pH dan waktu buang kapur terbaik menggunakan asam tartrat pada proses deliming kondisi asam serta pengaruhnya terhadap mutu kulit samak dan limbah cair yang terbentuk. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 2 faktor, yaitu pH dan lama waktu buang kapur dengan 3 kali ulangan. Masing – masing faktor terdiri 3 taraf, yaitu pH (4, 5, dan 6) dan waktu buang kapur (45, 60, dan 75 menit). Hasil analisis menunjukkan bahwa buang kapur pada pH 5 dan waktu 60 menit merupakan perlakuan terbaik. Dosis asam tartrat yang ditambahkan sebanyak 0.84 % dari bobot kulit yang digunakan. Perlakuan terbaik tersebut dapat menurunkan ketebalan kulit sebesar 49.49 % dan kadar kalsium pada kulit sebesar 46.99 %. Proses buang kapur dengan asam tartrat tidak mempengaruhi kualitas kulit samak yang dihasilkan. Sifat fisik, kimia dan mekanis kulit samak yang dihasilkan memenuhi SNI 4593:2011 sebagai bahan jaket kulit. Selain itu, limbah cair yang dihasilkan mengandung cemaran yang lebih rendah dibandingkan dengan buang kapur secara konvensional. Pelumatan merupakan tahapan yang dilakukan setelah buang kapur. Enzim merupakan bahan yang digunakan pada tahap pelumatan dalam proses penyamakan kulit. Enzim dan bahan kimia yang digunakan oleh industri penyamakan kulit di Indonesia umumnya adalah produk impor. Kondisi ini sangat mempengaruhi biaya produksi karena harga bahan impor tersebut cukup mahal dengan proporsi 0.93 % dari total biaya produksi. Selain itu, adanya pelemahan nilai tukar rupiah juga mempengaruhi finansial industri. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, penelitian ini mengkaji sintesis enzim yang digunakan pada tahap pelumatan. Enzim disintesis menggunakan Rhizopus sp dengan whey tahu sebagai substratnya. Waktu inkubasi terbaik yaitu 72 jam, dengan aktivitas enzim protease tertinggi sebesar 274.10 U/ml dan lipase sebesar 0.53 U/ml. Selanjutnya, enzim digunakan pada proses pelumatan. Rancangan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap dengan aktivitas enzim sebagai faktor tunggal (0, 2.5, 5, 7.5, dan 10 U/ml). Hasil analisis menunjukkan bahwa enzim yang dihasilkan mampu menghidrolisis protein pada kulit dan mengekstrak lemak yang ada di dalam kulit. Semakin tinggi aktivitas enzim yang digunakan, semakin tinggi protein terlarut dan lemaknya. Pada penelitian ini, perlakuan terbaik terdapat pada aktivitas 2.5 U/ml pada saat proses pelumatan. Kulit samak yang dihasilkan sangat baik, yakni kadar abu setelah dikurangi krom oksida ≤ 2 %, kadar krom oksida 3.01 %, suhu kerut 100.38 oC, kuat sobek 52.20 N/mm, kuat tarik 26.13 N/mm2 dan elongasi 48.63 %. Sifat – sifat kulit samak tersebut telah memenuhi SNI 4593:2011 sebagai bahan jaket kulit, hasil pengujian tersebut tidak berbeda nyata dengan perlakuan konvensional. Permasalahan pada proses penyamakan kulit adalah adanya penggunaan bahan yang berpotensi membahayakan lingkungan, yaitu krom sulfat. Krom sulfat menghasilkan kualitas kulit samak sangat baik yang dapat digunakan dalam berbagai jenis produk kulit sehingga umum digunakan di industri penyamakan kulit. Untuk meminimalkan penggunaan krom sulfat pada penyamakan kulit, salah satu caranya dengan mengkombinasikan bahan penyamak lain yang ramah lingkungan. Salah satu bahan yang dapat digunakan adalah silika dari abu sekam padi. Silika yang digunakan pada penelitian ini adalah natrium silikat (Na-silikat) dalam bentuk larutan. Hasil ekstraksi menunjukkan bahwa kandungan silika dalam larutan natrium silikat sebesar 3962 mg/l, sementara itu ukuran Na-silikat sebesar 138.83 nm (nanoNa-silikat). Ekstrak nanoNa-silikat yang dihasilkan digunakan sebagai bahan penyamak kombinasi. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap 2 faktor, yaitu larutan nanoNa-silikat (5, 10, 15, dan 20 %) dan krom sulfat (4, 5, 6, dan 7 %). Perlakuan terbaik pada penyamakan kombinasi ini terdapat pada dosis nanoNa-silikat 10 % dan krom sulfat 6 %. Kulit samak yang dihasilkan pada penyamakan kombinasi ini memiliki kualitas yang baik dan memenuhi SNI 4593:2011 sebagai bahan jaket kulit. Hasil pengujiannya adalah kekuatan sobek 59.93 N/mm, kekuatan tarik 40.23 N/mm2, dan elongasi 46.17 %. Penurunan dosis krom sulfat berpengaruh terhadap penurunan kandungan krom oksida pada kulit samak. Suhu kerut kulit samak dari penyamakan kombinasi ini (90.33 oC ) belum mencapai suhu kerut penyamakan krom sulfat, yaitu minimal 98.00 oC. Kulit pada perlakuan terbaik terlihat lebih cerah dibandingkan dengan kulit samak krom sulfat. Analisis menunjukkan bahwa cemaran limbah cair pada perlakuan terbaik lebih rendah dari pada penyamakan krom sulfat. Meskipun dosis krom sulfat telah diturunkan, namun penyamakan menggunakan krom masih berpotensi mencemari lingkungan karena Cr3+ pada krom sulfat dapat teroksidasi menjadi Cr6+ yang bersifat karsinogen genotoksik. Untuk menangani permasalahan tersebut, salah satu caranya adalah dengan mengganti bahan penyamak krom diganti dengan bahan penyamak nabati, misalnya mimosa. Mimosa telah banyak digunakan dalam proses penyamakan kulit, namun, mimosa merupakan produk impor yang cukup mahal sehingga mempengaruhi finansial industri. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan penyamakan kombinasi. Pada penelitian ini, mimosa dikombinasikan dengan nanoNa-silikat yang diperoleh dari ekstraksi abu sekam padi. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dua faktor, yaitu mimosa (10, 20, dan 30 %) dan Na-silikat (5, 10, 15, dan 20 %). Perlakuan terbaik pada penelitian ini adalah mimosa 20 % dan nanoNa-silikat 20 %. Sifat – sifat kulit samak yang dihasilkan sama dengan penyamakan konvensional mimosa. Sifat mekanik kulit samak perlakuan terbaik memenuhi IS (Indian standard) – 576 sebagai upper leather. Sifat mekanis tersebut tidak berbeda nyata dengan penyamakan dengan mimosa, namun mutunya masih dibawah penyamakan krom sulfat. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kuat sobek 39.98 N/mm, kuat tarik 26.42 N/mm2, elongasi 41 %, dan suhu kerut 84 oC. Warna kulit samak kombinasi lebih cerah dibandingkan kulit samak mimosa. Limbah cair yang dihasilkan lebih baik pada parameter COD dan TSS dan secara umum lebih baik dari penyamakan krom sulfat. Penurunan kadar cemaran pada setiap perlakuan terbaik berkontribusi terhadap penurunan emisi dari proses penyamakan kulit. Beberapa emisi yang timbul dari proses penyamakan kulit adalah gas rumah kaca (GRK), asidifikasi dan eutrofikasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa rekayasa penyamakan kulit yang dilakukan dapat menurunkan emisi yang terbentuk selama proses penyamakan. Kemudian, analisis nilai tambah menunjukkan bahwa perlakuan terbaik memberikan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan konvensional |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/106518 |
| Appears in Collections: | DT - Agriculture Technology |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Revisi draft disertasi _pasca ujian terbuka4-fix.pdf Restricted Access | Full disertasi | 6.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ringkasan-abstrak.pdf Restricted Access | Ringkasan/abstrak | 5.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Pendahuluan.pdf Restricted Access | Pendahuluan | 5.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Tinjauan Pustaka.pdf Restricted Access | Tinjauan pustaka | 5.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Metodelogi.pdf Restricted Access | metodelogi penelitian | 5.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Hasil dan pembahasan.pdf Restricted Access | Hasil dan pembahasan | 7.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Kesimpulan dan saran.pdf Restricted Access | Kesimpulan dan saran | 5.41 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.